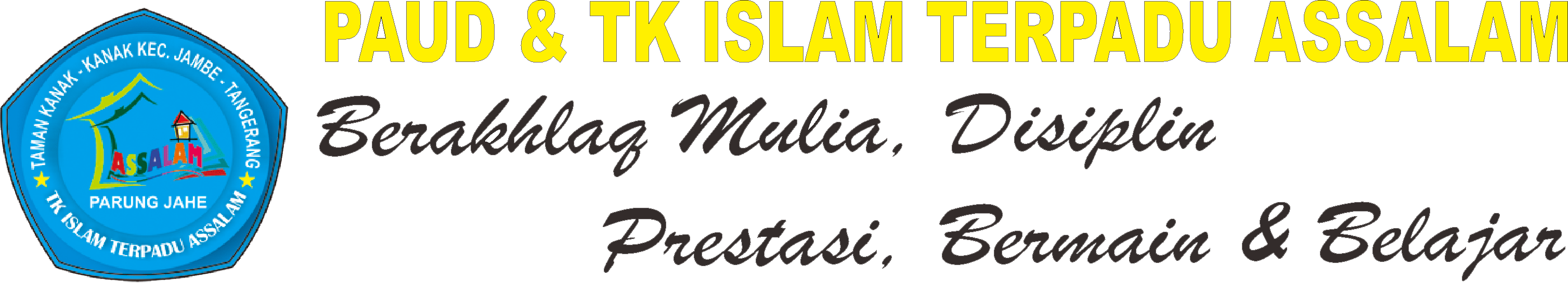Artikel Tentang Kurikulum Merdeka
”Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak”. (Ki Hajar Dewantara)
Sebetulnya, fokus kita saat ini bukan perihal bagaimana semua harus melaksanakan Kurikulum Merdeka karena jelas satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kurikulum apa yang akan diterapkan.
Artinya, masih akan ada satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum 2013 atau bahkan Kurikulum 2013 yang disederhanakan (kondisi khusus/darurat-red).
Namun demikian, berdasar pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dijadikan dasar filosofi pendidikan Indonesia, bahwa kita haruslah memandang murid bukan sebagai botol kosong melainkan sebagai individu yang memang secara kodrati memiliki potensi.
Karenanya, proses interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama murid hakikatnya adalah sebuah proses dimana guru membantu dan menuntun murid dalam mencapai kompetensi.
Sehingga, proses pembelajaran tidaklah lagi dimaknai sebagai upaya mengejar target ketuntasan kurikulum melainkan lebih kepada sebagai upaya untuk selalu membantu, menuntun, dan melayani murid dalam mencapai kompetensi.
Potensi yang dimiliki oleh setiap murid jelaslah tidak selalu sama. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menganalogikan murid ibarat benih padi dan benih jagung serta guru ibarat petani yang menanam benih-benih tersebut.
Akankah benih padi yang ditanam tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya benih jagung yang ditanam tumbuh menjadi padi? Tentu saja tidak. Benih padi akan tetap tumbuh menjadi padi sebagaimana benih jagung yang ditanam juga akan tumbuh menjadi jagung.
Namun, akankah ketika benih padi yang ditanam tersebut tumbuh menjadi padi yang subur? Atau akankah ketika benih jagung yang ditanam tersebut tumbuh menjadi jagung yang subur? Jawabannya barangkali belum tentu. Karena itu semua akan sangat tergantung bagaimana petani melakukan proses perawatan terhadap kedua jenis tanaman itu.
Begitupula-lah guru bersama murid-muridnya.
Akankah para murid sebagai benih dinamis dengan keragaman potensi yang milikinya berkembang dengan baik atau tidak sangat tergantung kepada gurunya.
Kendati memang guru tidak dapat mengubah kodrat dasar yang telah murid miliki, namun sangat berperan dalam memberikan perlakuan yang baik kepada mereka dan menuntun menghindarkan mereka dari pengaruh tidak baik yang akan merusak kodrat potensi yang dimilikinya.
Guru senantiasa memahami bahwa pada dasarnya muridnya merupakan individu-individu yang berbeda baik karakteristiknya, gaya belajarnya, keadaan keluarganya, daya dukung ekonominya, tingkat intelegensi kognitif-nya, minatnya, bakatnya, serta hal-hal berbeda lainnya.
Maka atas keragaman tersebut, guru haruslah mampu menerima semuanya secara inklusif untuk selanjutnya memberikan perlakuan beragam yang tepat terhadap setiap muridnya. Jangan paksa murid yang beragam tersebut melalui proses pembelajaran yang seragam. Inilah yang disebut sebagai praktik pembelajaran berdiferensiasi.
Lantas upaya apa yang harusnya dilakukan oleh guru untuk dapat mengetahui secara mendalam keragaman yang dimiliki oleh setiap murid? Lakukanlah proses asemen diagnostik kognitif dan non-kognitif.
Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan sebelum merancang pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif setiap murid. Melalui upaya tersebut, guru selanjutnya diharapkan mampu memberikan perlakuan pada proses pembelajaran dengan tingkat capaian yang disesuaikan dengan kemampuan awal setiap murid terlebih dahulu. Itupulalah alasan kenapa kita seharusnya membelajarkan murid sesuai dengan fase-nya (teaching at the right level).
Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen untuk mengetahui keadaan kesejahteraan psikologi, pergaulan, keadaan keluarga, dan gaya belajar murid. Dengan mengetahui keadaan-keadaan tersebut selayaknya kita sebagai guru sadar akan apa yang harus kita lakukan dalam melayani dan menuntut para murid kita melalui proses pembelajaran.
Lantas bagaimana kita dapat mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran? Tentu saja dengan cara melakukan asesmen. Hanya saja orientasi makna asesmen yang diterapkan haruslah diubah.
Apa yang selama ini biasa dilakukan berupa asesmen pada akhir proses pembelajaran (assessment of learning) haruslah mulai digeser ke dalam bentuk asesmen sebagai pembelajaran (assessment as learning) dan asesmen untuk pembelajaran (assessment for learning).
Jika asesmen pada akhir proses pembelajaran yang kita kenal sebagai asesmen sumatif, diarahkan pada asesmen untuk evaluasi pada akhir pembelajaran, maka asesmen sebagai pembelajaran dan asesmen untuk pembelajaran yang kita kenal sebagai asesmen formatif, diarahkan sebagai bahan refleksi dan perbaikan pembelajaran.
Untuk itu, makna ketuntasan belajar tidak lagi sepenuhnya terletak pada data berbentuk angka kuanitatif melainkan lebih menitikberatkan pada data berbentuk kualitatif. Sehingga nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam bentuk angka nampaknya tidaklah lagi relevan.
Kembali pada konteks penerapan kurikulum, bahwa sebagaimana disampaikan di atas bahwa fokus kita bukan tentang bagaimana semuanya harus menerapkan Kurikulum Merdeka melainkan tentang bagaimana para guru melakukan pembaharuan proses pembelajaran.
Pemerintah sendiri mengistilahkan pembaharuan ini sebagai proses Pembelajaran Paradigma Baru. Silahkan pilih bentuk kurikulum apa yang sesuai dan akan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing, Kurikulum 2013, Kurikulum Kondisi Khusus, atau Kurikulum merdeka, silahkan! Namun demikian, apapun kurikulumnya pembelajarannya harus berupa Pembelajaran Paradigma Baru.
Pembelajaran Paradigma Baru, sebagaimana sebagian uraiannya telah tersampaikan pada uraian di atas, dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid menyesuaikan konteks kehidupan, serta mengarah pada masa depan.

Guru Penggerak Angkatan 7
Konsep “Guru Penggerak” di Indonesia mengacu pada guru yang berperan penting dalam mendorong perkembangan pendidikan dan mendorong perubahan positif di berbagai aspek masyarakat.